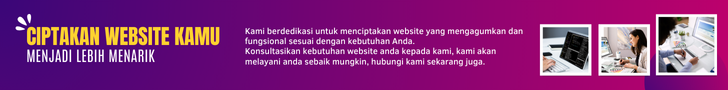Rabu,08 Oktober 2025
Fenomena UGC mengaburkan dikotomi klasik antara “pencipta,” “konsumen,” dan “pelanggar,” melahirkan peran hibrida yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh kerangka hukum hak cipta tradisional.
Evolusi lanskap digital, yang dikatalisasi oleh arsitektur partisipatoris Web 2.0, telah melahirkan sebuah fenomena sosio-teknis yang fundamental: User-Generated Content (UGC).
UGC, yang didefinisikan sebagai ragam konten—mulai dari teks, gambar, audio, hingga video, yang diciptakan dan didiseminasikan secara sukarela oleh pengguna, bukan oleh entitas profesional, telah merekonfigurasi secara radikal paradigma produksi dan konsumsi informasi.
Karakteristik inheren UGC terletak pada otentisitas, kredibilitas, dan pengaruhnya yang organik, yang secara diametral berlawanan dengan konten yang diproduksi secara komersial.
Transformasi dari forum berbasis teks ke ekosistem multimedia imersif seperti YouTube dan TikTok tidak hanya memperluas skala UGC, tetapi juga memperdalam kompleksitas yuridisnya.
Pada titik inilah terjadi friksi doktrinal yang inheren dan mendalam. Arsitektur hukum hak cipta modern, yang secara historis dibangun di atas postulat pencipta tunggal (single author) dan penganugerahan hak eksklusif, baik hak moral maupun hak ekonomi—mengalami disrupsi fundamental oleh natur UGC yang kolaboratif, derivatif, dan transformatif.
Fenomena UGC mengaburkan dikotomi klasik antara “pencipta,” “konsumen,” dan “pelanggar,” melahirkan peran hibrida yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh kerangka hukum hak cipta tradisional.
Permasalahan ini bukan lagi sekadar isu komersial periferal, seperti penggunaan musik berhak cipta dalam ulasan produk, melainkan telah menjadi isu sentral di mana tindakan ekspresi kreatif itu sendiri—sebuah video reaksi, sebuah parodi, atau sebuah remix—secara prima facie merupakan karya derivatif yang berpotensi melanggar hak cipta.
Tesis sentral artikel ini adalah bahwa kerangka hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menderita suatu “kekosongan norma” (normative vacuum) yang kritis terkait pengaturan tanggung jawab hukum intermediaris (intermediary liability) untuk platform digital berbasis UGC.
Kevakuman ini menjadikan UUHC tidak efektif dalam merespons dinamika ekosistem digital kontemporer.
Untuk mengelaborasi defisiensi ini dan memformulasikan rekomendasi de lege ferenda, artikel ini akan menyajikan analisis yuridis-komparatif yang rigor terhadap dua paradigma global yang dominan: model imunitas bersyarat (conditional immunity) melalui mekanisme safe harbor dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat, dan model liabilitas primer (primary liability) yang proaktif dalam Directive on Copyright in the Digital Single Market (DSM Directive) Artikel 17 Uni Eropa.
Permasalahan
Analisis dalam artikel ini dipandu oleh tiga rumusan masalah yuridis yang fundamental, yang dirancang untuk mengupas ketegangan doktrinal dan sistemik yang menjadi inti persoalan:
1.Bagaimana sifat sui generis dari UGC—yang secara inheren bersifat derivatif, transformatif, dan partisipatoris—mendekonstruksi dikotomi klasik antara “Pencipta” dan “Pengguna” dalam arsitektur hukum hak cipta, dan apa implikasinya terhadap doktrin orisinalitas, hak moral, serta hak ekonomi?
2.Sejauh mana UUHC No. 28 Tahun 2014, dengan “kekosongan norma” yang teridentifikasi dan kerangka penegakan hukum yang bersifat reaktif-konvensional, mampu secara adekuat meregulasi liabilitas platform digital sebagai fasilitator utama ekosistem UGC dan menyeimbangkan hak-hak para pemangku kepentingan secara proporsional?
3.Apa divergensi filosofis, operasional, dan implikasi sistemik yang fundamental antara model imunitas bersyarat Amerika Serikat melalui DMCA safe harbor dengan model liabilitas primer Uni Eropa melalui DSM Directive Artikel 17, terutama dalam dampaknya terhadap inovasi platform, kebebasan berekspresi pengguna, dan efektivitas proteksi hak cipta?
Pembahasan
Dialektika Doktrinal: Hak Cipta Tradisional Vis-à-Vis Kreativitas Transformatif UGC
Di tengah benturan antara eksklusivitas hak cipta dan fluiditas kreativitas digital, doktrin fair use dalam yurisdiksi Amerika Serikat muncul sebagai katup pengaman krusial yang melegitimasi eksistensi ekosistem UGC.
Doktrin ini, yang dikodifikasikan dalam 17 U.S.C. § 107, menyediakan kerangka analisis berbasis empat faktor untuk menentukan apakah suatu penggunaan karya berhak cipta tanpa izin dapat dibenarkan: (1) tujuan dan karakter penggunaan; (2) sifat karya asli; (3) jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan; dan (4) dampak penggunaan terhadap pasar potensial karya asli.
Dalam yurisprudensi modern, faktor pertama, khususnya konsep “penggunaan transformatif” (transformative use), telah menjadi pertimbangan yang paling determinan.
Suatu penggunaan dianggap transformatif jika ia “menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda, dan tidak menjadi substitusi bagi penggunaan karya asli”.
Berbagai bentuk UGC, seperti parodi, kritik, komentar, peliputan berita, dan budaya remix, secara inheren bersifat transformatif karena mereka tidak sekadar mereproduksi, melainkan mengontekstualisasikan ulang, mengkritik, atau membangun narasi baru di atas karya yang sudah ada. Tanpa doktrin ini, aktivitas inti yang menopang platform seperti YouTube dan TikTok—yang esensinya adalah komentar dan derivasi budaya—secara hukum tidak dapat dipertahankan, karena hampir setiap kontennya akan dianggap sebagai pelanggaran hak derivatif.
Dengan demikian, fair use bukanlah sekadar pengecualian insidental, melainkan pilar doktrinal yang menopang legitimasi hukum dari seluruh web partisipatoris.
Meskipun demikian, aplikasi doktrin ini menghadapi tantangan signifikan. Sifatnya yang subjektif dan diputuskan berdasarkan kasus per kasus (case-by-case basis) menciptakan ambiguitas.
Sistem moderasi konten otomatis, seperti Content ID milik YouTube, secara teknis tidak mampu melakukan analisis fair use yang kontekstual dan bernuansa. Akibatnya, sistem ini cenderung melakukan pemblokiran berlebih (over-blocking), yang kemudian memerlukan proses banding dan peninjauan manusia untuk menyelesaikan sengketa, menunjukkan keterbatasan solusi teknokratis dalam menghadapi masalah doktrinal yang kompleks.
Komparasi Rezim Tanggung Jawab Intermediaris: Safe Harbor vs. Proactive Filtering
Komunitas internasional telah merespons tantangan UGC dengan dua model regulasi liabilitas intermediaris yang secara fundamental berbeda, merefleksikan filosofi kebijakan yang kontras.
Model Amerika Serikat, yang termaktub dalam DMCA § 512, mengadopsi pendekatan imunitas bersyarat dengan mekanisme reaktif. Filosofi dasarnya adalah untuk melindungi inovasi dan pertumbuhan industri internet dengan memberikan “pelabuhan aman” (safe harbor) bagi Penyedia Layanan Daring (OSP) dari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan penggunanya.
Beban utama diletakkan pada pemegang hak cipta untuk secara aktif mengidentifikasi pelanggaran dan mengirimkan notifikasi penghapusan (takedown notice) yang valid. Kewajiban OSP adalah untuk “bertindak cepat” (act expeditiously) menghapus konten tersebut setelah menerima notifikasi.
Model ini, yang juga mencakup mekanisme notifikasi tanggapan (counter-notification), terbukti instrumental dalam memfasilitasi ledakan platform UGC. Namun, ia dikritik keras karena menciptakan “kesenjangan nilai” (value gap), di mana platform meraup keuntungan dari konten ilegal selama jeda waktu antara pengunggahan dan pelaporan, sementara kompensasi bagi pencipta minimal.
Putusan penting seperti dalam kasus BMG v. Cox menunjukkan bahwa kegagalan platform dalam menindak pelanggar berulang secara sistematis dapat menyebabkan hilangnya proteksi safe harbor.
Sebaliknya, model Uni Eropa dalam DSM Directive Artikel 17 merepresentasikan pergeseran paradigma menuju liabilitas primer dengan tanggung jawab proaktif. Tujuannya adalah untuk menutup “kesenjangan nilai” dengan menyatakan bahwa Penyedia Layanan Berbagi Konten Daring (OCSSP) secara langsung melakukan “tindakan komunikasi kepada publik” dan bertanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna.
Untuk menghindari liabilitas, OCSSP harus menunjukkan “upaya terbaik” (best efforts) untuk: (a) memperoleh lisensi dari pemegang hak, (b) memastikan ketidaktersediaan karya ilegal yang informasinya telah diberikan oleh pemegang hak, dan (c) setelah notifikasi, menghapus konten dan mencegah pengunggahannya kembali di masa depan (notice-and-staydown).
Secara praktis, kewajiban “upaya terbaik” dan “staydown” ini secara de facto mengharuskan implementasi teknologi penyaringan konten otomatis (upload filters). Hal ini memicu kekhawatiran serius akan potensi penyensoran dan efek mengerikan (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi, karena filter otomatis tidak dapat secara akurat membedakan antara penggunaan yang melanggar dan penggunaan yang sah (misalnya, parodi).
Meskipun Pengadilan Uni Eropa (CJEU) telah menguatkan validitas Artikel 17, pengadilan menekankan pentingnya penerapan perlindungan (safeguards) yang memadai untuk menyeimbangkan hak cipta dengan kebebasan berekspresi.
Posisi Hukum Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Kekosongan Normatif
Di tengah dialektika global ini, posisi hukum Indonesia berada dalam kondisi ambiguitas yang problematis. UUHC No. 28 Tahun 2014, meskipun telah mengakui karya digital sebagai objek perlindungan dan menganut prinsip perlindungan otomatis (declaratory principle) atas hak moral dan ekonomi, gagal menyediakan kerangka kerja yang spesifik untuk liabilitas intermediaris digital. Penelitian yuridis secara eksplisit mengonfirmasi adanya “kekosongan norma” dalam UUHC terkait platform berbasis UGC.
Ketentuan yang ada, seperti Pasal 10 (larangan bagi pengelola tempat usaha) dan Pasal 114 (sanksi pidana bagi pengelola tempat perdagangan), dirancang untuk dunia fisik dan properti berwujud. Upaya untuk menafsirkannya secara ekstensif ke ranah virtual terbukti tidak koheren dan tidak memadai.
Kegagalan hukum Indonesia bersifat konseptual: ia masih mencoba menerapkan kerangka berbasis “properti” yang mengatur “benda” di pasar fisik, pada masalah “tata kelola” yang seharusnya meregulasi “aliran informasi” di platform digital.
Berbeda dengan DMCA atau Artikel 17 yang menetapkan proses tata kelola konten dalam skala besar, UUHC hanya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional (gugatan perdata atau delik aduan pidana) yang lambat dan tidak praktis untuk menangani volume UGC yang masif.
Konsekuensi sistemik dari kevakuman ini sangat merugikan. Pertama, penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif, meletakkan beban yang tidak proporsional pada pencipta individu untuk memonitor pelanggaran.
Kedua, ketidakpastian hukum yang dihasilkan menghambat inovasi dan investasi dalam pengembangan platform digital domestik. Ketiga, tanpa perlindungan hukum yang jelas, baik hak ekonomi pencipta maupun hak pengguna untuk melakukan penggunaan transformatif yang sah menjadi rentan. Akibatnya, tata kelola konten di Indonesia secara de facto diatur bukan oleh hukum nasional, melainkan oleh kebijakan internal platform global yang didasarkan pada kepatuhan mereka terhadap rezim hukum asing seperti DMCA.
Kesimpulan
Analisis yuridis ini menyimpulkan bahwa fenomena UGC menghadirkan tantangan doktrinal fundamental bagi hukum hak cipta klasik. Komunitas internasional merespons dengan dua model liabilitas intermediaris yang divergen: pendekatan reaktif Amerika Serikat yang memprioritaskan inovasi platform, dan pendekatan proaktif Uni Eropa yang mengutamakan proteksi ekonomi bagi pemegang hak.
Di tengah spektrum ini, kerangka hukum Indonesia dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 menunjukkan defisiensi kritis berupa kekosongan norma yang menciptakan ketidakpastian hukum sistemik dan penegakan yang tidak efektif bagi seluruh pemangku kepentingan.
Mempertahankan status quo adalah pilihan yang tidak dapat dipertahankan. Indonesia dihadapkan pada sebuah pilihan kebijakan yang fundamental, di mana adopsi mentah-mentah salah satu model global bukanlah solusi yang bijaksana. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Indonesia melakukan reformasi legislatif untuk merumuskan sebuah rezim sui generis yang seimbang.
Sebagai rekomendasi de lege ferenda, Indonesia perlu mengembangkan mekanisme safe harbor yang terinspirasi dari kejelasan prosedural “notice-and-takedown” DMCA untuk memberikan kepastian hukum bagi inovator dan melindungi kebebasan berekspresi.
Namun, mekanisme ini harus dilengkapi dengan elemen tanggung jawab yang lebih kuat bagi platform komersial berskala besar, yang dapat mencakup kewajiban untuk menyediakan alat identifikasi konten (serupa Content ID) untuk memfasilitasi opsi monetisasi atau penghapusan bagi pemegang hak pasca-pengunggahan, bukan sebagai alat penyaringan preventif.
Yang terpenting, undang-undang baru ini harus secara eksplisit mengakui dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penggunaan transformatif yang sah, seperti parodi, kritik, dan komentar. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan solusi hukum yang modern, berimbang, dan sesuai dengan konteks nasional untuk menjawab tantangan global UGC.
Penulis: Bony Daniel